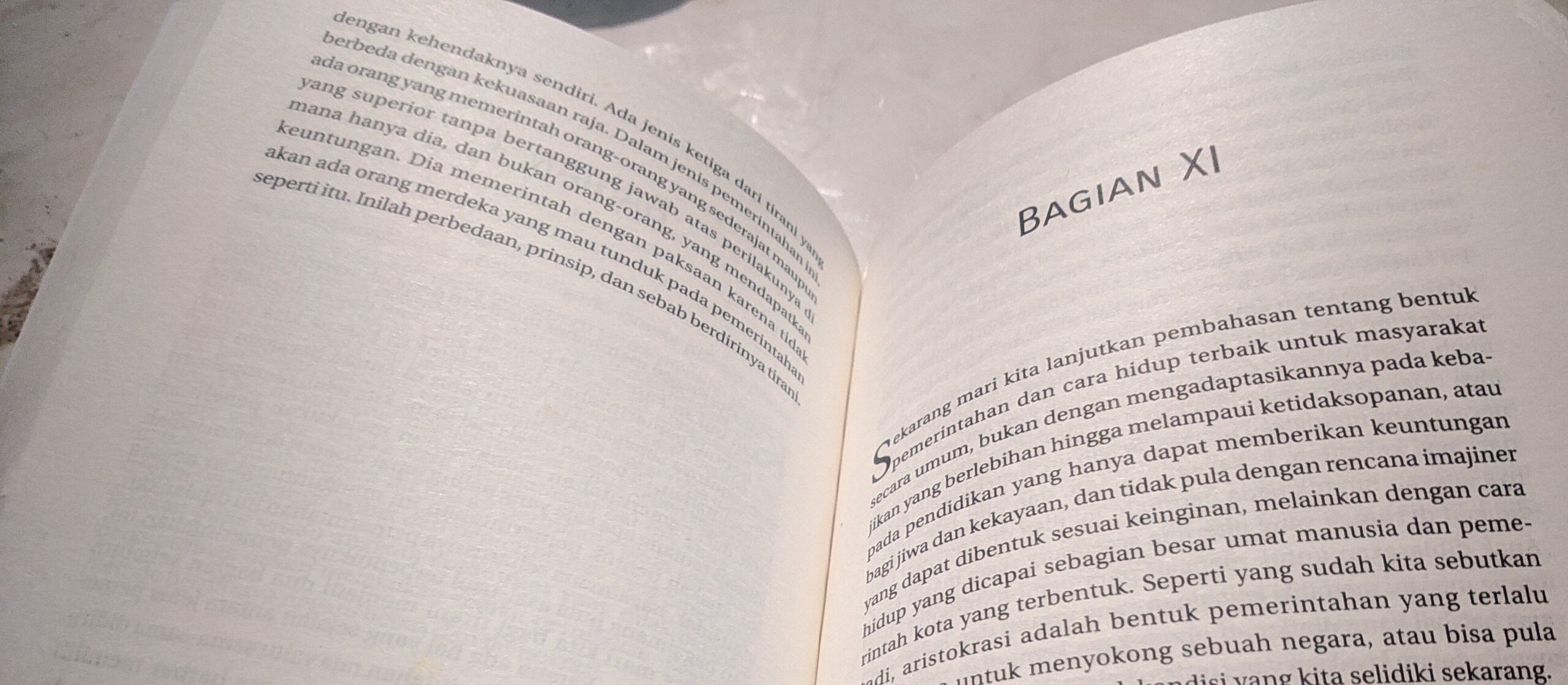Suaraamor.com. Tulisan kali ini saya beri judul “mendengarkan bukan berarti Anda membaca”, ini menegaskan bahwa mendengarkan dan membaca adalah dua proses yang berbeda, yang melibatkan cara kerja otak dan fokus yang tidak sama. Meskipun keduanya merupakan cara untuk menyerap informasi.
Hari ini, pengetahuan dapat diakses melalui layar ponsel hanya dengan bermodalkan menyentuh ikon aplikasi, muncul sebuah kebiasaan baru, yaitu orang lebih senang mendengarkan dibanding membaca. Video pendek TikTok, potongan ceramah YouTube, podcast singkat, dan reels Instagram telah menjadi sumber utama informasi bagi banyak kalangan. Dengan segala kemudahannya, kita seakan merasa telah belajar cukup banyak dalam waktu singkat. Akan tetapi, di balik semua itu tersembunyi sebuah problem besar, dimana mendengarkan tidak pernah sama dengan membaca.
Perubahan cara kita menyerap pengetahuan ini menciptakan jarak antara informasi dan pemahaman. Mendengarkan memang memberikan sensasi cepat mengerti, tetapi sensasi itu sering menipu. Ia memberikan perasaan bahwa kita telah memahami sesuatu, padahal yang terjadi justru sebaliknya. Kita, pada dasarnya hanya menerima suara, bukan gagasan utuh (lengkap). Kita menyerap kesimpulan, bukan proses berpikirnya.
Dalam tradisi keilmuan Islam klasik, mendengarkan memang memiliki tempat. Para ulama hadis melakukan samā’, mendengarkan bacaan guru dengan penuh kesungguhan. Tetapi proses mendengarkan itu tidak berdiri sendiri. Ia selalu terikat dengan teks, ditopang oleh naskah yang dibaca, diverifikasi, dicatat, dan diulang. Mendengar adalah bagian dari literasi, bukan penggantinya. Hari ini, mendengar berdiri sendirian, dia terputus dari teks, tidak didampingi pembacaan, bahkan sering menggantikan membaca itu sendiri.
Di sinilah letak persoalan epistemologis yang serius. Suara terus bergerak, tetapi akal tidak dipaksa untuk berhenti mencerna. Ketika seseorang membaca, ia harus memperhatikan kata demi kata, kalimat demi kalimat atau mungkin huruf demi huruf. Pembaca dapat berhenti, merenung, menandai, dan mengulang apabila ada bacaan yang kurang dimengerti. Membaca memaksa kita melakukan kerja mental tingkat super tinggi, karena kita berusaha untuk memahami, menganalisis, mengevaluasi, dan menghubungkan-nya. Dalam kacamata psikologi kognitif, aktivitas ini disebut sebagai deep processing, yaitu proses berpikir mendalam yang membentuk pengetahuan yang lebih kokoh dan tahan lama (nempel di otak).
Sebaliknya, mendengarkan hanya membawa kita pada surface processing, yaitu informasi lewat, tetapi jarang tinggal di ingatan kita. Kita mungkin saja merasa paham saat itu juga, tetapi pemahaman itu cepat hilang. Bahkan lebih berbahaya lagi, sering muncul ilusi pengetahuan, yaitu perasaan bahwa kita menguasai sesuatu padahal kita hanya mengingat ringkasan pendek yang diucapkan dengan penuh percaya diri oleh seorang pembicara.
Fenomena ini kini begitu nyata. Kita melihat banyak orang mungkin merasa cukup mengetahui suatu isu hanya dengan menonton video satu menit, dua menit, atau bahkan ber jam jam. Banyak yang merasa mampu berbicara tentang agama, politik, filsafat, sosiologi atau psikologi hanya dari potongan ceramah pendek atau materi lewat YouTube. Inilah generasi yang pengetahuannya cepat datang, tetapi tidak punya akar. Ia tumbuh di permukaan, rapuh, dan mudah goyah. Mereka hafal kesimpulan, tetapi tidak pernah membaca argumentasinya.
Kelemahan dalam kemampuan analisis menjadi dampak sosial-intelektual yang paling terasa. Tanpa membaca, seseorang sulit menjabarkan alasan di balik pendapatnya. Ia hanya mengulang apa yang ia dengar. Dalam perdebatan, ia cepat tersinggung karena tidak memiliki struktur logika yang kuat. Karena tanpa teks, kita kehilangan alat untuk berpikir kuat. Kita menjadi pengikut suara, bukan pemilik gagasan.
Lebih jauh, budaya mendengarkan tanpa membaca membuat masyarakat mudah dipengaruhi. Suara yang lantang dianggap benar. Video yang viral dianggap ilmiah. Padahal kebenaran tidak pernah lahir dari kecepatan viralnya informasi, tetapi dari kedalaman kajian. Tanpa fondasi membaca, kita rentan terseret opini publik, propaganda digital, atau narasi emosional yang sengaja dikemas untuk memengaruhi.
Dalam perjalanan panjang sejarah peradaban, membaca selalu menjadi fondasi. Ulama-ulama besar membangun ilmu dengan membaca, menulis, dan merenung dalam kesunyian. Al-Ghazali tidak menjadi al-Ghazali hanya dengan mendengar. Ibn Rushd, al-Farabi, Ibn Sina, bahkan Nurcholish Madjid dan Harun Nasution pun mereka semua adalah pembaca yang tekun, bukan sekadar pendengar yang rajin. Dunia berubah, tetapi prinsip ini tidak pernah usang, bahwa tidak ada kedalaman tanpa membaca.
Tentu saja, mendengarkan tetap bermanfaat. Suara memiliki kekuatan untuk menggerakkan hati, memotivasi, dan memperjelas. Tetapi mendengarkan baru menjadi sempurna ketika ia datang setelah membaca. Ketika teks telah dipahami, mendengar menjadi proses internalisasi yang memperkuat. Ketika membaca mendahului, mendengarkan menjadi cahaya tambahan. Tetapi jika mendengar berdiri tanpa teks, ia hanya menjadi suara kosong yang lewat begitu saja.
Derasnya arus informasi instan, kita perlu kembali merawat martabat membaca. Karena peradaban tidak dibangun oleh video pendek, tetapi oleh teks yang direnungkan. Pemikiran tidak lahir dari mendengarkan yang serba cepat, tetapi dari membaca yang sabar dan mendalam. Mendengarkan memberi kita informasi, tetapi membaca memberi kita pemahaman. Mendengarkan mempercepat, tetapi membaca memperdalam. Mendengarkan menyenangkan, tetapi membaca membentuk watak intelektual.
Jika kita ingin melahirkan generasi pemikir Muslim yang matang, kritis, dan berintegritas, maka kebiasaan membaca harus kembali menjadi tradisi. Suara bisa memudar, tetapi teks adalah ingatan yang abadi. Dan di dunia yang bergerak cepat ini, hanya mereka yang mau berhenti sejenak untuk membaca yang akan mampu memahami dunia dengan lebih jernih.
Serang Banten, 17 November 2025
Aceng Murtado